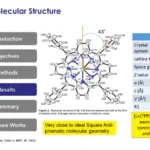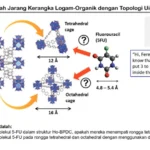Peneliti BRIN Jelaskan Inovasi Material untuk Masker, Sintesis Karbon Microsphere dari Gondorukem
Tangerang Selatan – Humas BRIN. Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (ORNM) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menggelar webinar rutin ORNAMAT dengan judul “Sintesis Karbon Microsphere dari Prekursor Getah Pinus (Gondorukem) dengan Metode Spray Pyrolysis”, pada Selasa (07/11). Pada kesempatan tersebut, Peneliti Pusat Riset Material Maju (PRMM) BRIN, Jayadi, menyoroti aplikasi teknologi karbon, termasuk…