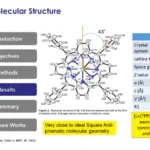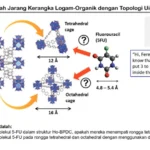BRIN Kenalkan Dua Aplikasi Riset Permukaan untuk Implan Gigi dan Deteksi Bakteri
Tangerang Selatan – Humas BRIN. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material (ORNM) mengenalkan dua aplikasi riset permukaan untuk implan gigi dan deteksi bakteri. Kedua aplikasi riset tersebut diulas pada webinar ORNAMAT seri kelima, Selasa (28/6). Kedua aplikasi riset permukaan tersebut yakni Aplikasi Teknologi Sandblasted with Large Grit and Acid-etched (SLA) dalam Modifikasi…