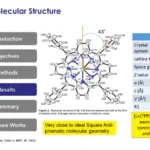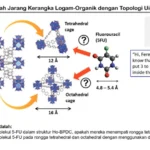Aktivitas Tambang Nikel di Morowali, Periset BRIN Kaji Dampaknya terhadap Kualitas Air Sungai
Tangerang Selatan – Humas BRIN. Peneliti Kelompok Riset Eksplorasi Pertambangan, Pusat Riset Teknologi Pertambangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Muhammad Razzaaq Al Ghiffari mengkaji pengaruh perubahan tutupan lahan pada area pertambangan nikel, ditinjau dari aspek hidrologi, di Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut Ghiffari, adanya pembukaan lahan karena perkebunan, longsoran, maupun aktivitas tambang menyebabkan reaksi kimia…